Oleh: Dini Koswarini
Belakangan ini istilah job hugging semakin sering kita dengar di kalangan pemuda. Istilah Job hugging menggambarkan kecenderungan pekerja untuk tetap bertahan di pekerjaan mereka sekarang, meskipun sudah kehilangan minat, motivasi, bahkan kenyamanan. Pilihannya sederhana, bertahan dengan mencari aman atau mengambil risiko hengkang di tengah ekonomi yang serba tak pasti.
Bukan hanya di Indonesia, bahkan para pekerja di Amerika Serikat mencatat bahwa tingkat pekerja yang secara sukarela meninggalkan pekerjaannya berada di angka sekitar 2%. Angka ini masuk kategori terendah sejak 2016, yang menunjukkan bahwa orang semakin enggan pindah pekerjaan.
Selain itu, proporsi pencari kerja yang yakin bahwa banyak pekerjaan tersedia di pasar menurun dari 26 % menjadi 38 %, sebuah indikator pesimisme di kalangan pekerja. (detikfinance, 20/9/2025)
Salah satu suara akademis yang menyoroti fenomena ini ialah Profesor Tadjuddin Noer Effendi dari UGM. Ia menyebut bahwa job hugging muncul sebagai efek dari ketidakpastian pasar kerja. Sehingga lulusan perguruan tinggi merasa terjebak dalam pekerjaan yang 'aman' demi keamanan finansial dan stabilitas, karena pandangan mereka, "Lebih baik asal kerja daripada menjadi pengangguran intelektual.” (Universitas Gadjah Mada, 22/9/2025)
Kalau kita lihat lebih dalam, job hugging bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan gejala kegagalan sistemik dalam dunia kerja modern. Kapitalisme global gagal menjamin pekerjaan yang layak bagi semua orang. Bahkan bisa dikatakan dengan kondisi saat ini, negara semakin melepas tanggung jawab menyediakan lapangan kerja dan justru menyerahkan urusan itu pada swasta.
Padahal, ketika swasta terhimpit krisis, langkah pertama yang mereka ambil biasanya adalah mengurangi perekrutan atau bahkan melakukan PHK. Di sinilah rakyat terjepit sebab mereka tidak punya jaring pengaman selain pekerjaan yang sedang mereka jalani, betapapun tidak nyamannya.
Lebih jauh lagi, kita juga melihat bagaimana sumber daya alam dan modal terkonsentrasi pada segelintir kapitalis dengan izin negara. Situasi ini membuat kesempatan masyarakat luas untuk mengakses pekerjaan produktif semakin sempit.
Sementara itu, perekonomian yang makin bergeser ke arah sektor non-riil seperti perdagangan finansial, instrumen ribawi, hingga spekulasi pasar tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Akibatnya, lapangan kerja nyata semakin terbatas, dan rakyat terpaksa 'memeluk' pekerjaan seadanya.
Ironisnya, sistem pendidikan tinggi pun diarahkan agar adaptif terhadap dunia kerja, seolah-olah cukup menyesuaikan diri dengan pasar sudah bisa menyelesaikan masalah. Namun faktanya, liberalisasi perdagangan jasa membuat negara lepas tangan.
Lulusan kampus dilepaskan begitu saja ke pasar tenaga kerja tanpa ada jaminan mereka bisa benar-benar terserap. Jadi, job hugging muncul bukan karena pekerja malas mengambil risiko, akan tetapi karena sistem mendorong mereka berada di posisi serba sulit.
Fenomena ini tentu punya konsekuensi serius. Sebab stagnasi karir tak terhindarkan ketika seseorang terus bertahan di pekerjaan yang tidak lagi memberi ruang berkembang. Keterampilan yang dimiliki perlahan usang, daya saing menurun.
Dari sisi psikologis, rasa jenuh dan keterpaksaan bisa menggerogoti kesehatan mental. Bahkan dari sisi organisasi, kondisi ini sangat merugikan. Sebab ketika mobilitas talenta mandek, perusahaan kehilangan kesempatan untuk menyerap energi baru dan berinovasi. Lebih parah lagi, generasi muda yang baru lulus akhirnya semakin sulit masuk pasar kerja, sehingga kesenjangan makin melebar.
Di titik ini, kita perlu kembali pada pertanyaan mendasar, jadi siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas penyediaan lapangan kerja?
Dalam pandangan Islam, jawabannya jelas yakni negara. Negara punya kewajiban utama mengurus rakyatnya, termasuk memastikan ketersediaan pekerjaan yang layak.
Negara tidak boleh hanya menjadi fasilitator modal, apalagi sekadar penonton. Ia harus aktif mengelola sumber daya alam, membangun industrialisasi, membuka lahan produktif, memberikan akses modal, serta melatih keterampilan rakyat agar siap bekerja.
Lebih jauh lagi, dalam Islam, pendidikan dan pekerjaan bukan hanya urusan ekonomi. Keduanya berada dalam satu dibingkai dengan nilai ibadah.
Sehingga orang bekerja bukan sekadar mencari uang, melainkan memenuhi kewajiban hidup dengan standar halal-haram. Negara pun melayani urusan rakyatnya dengan semangat ibadah, bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi. Inilah yang membedakan antara Islam dengan Kapitalisme yakni ada keterikatan spiritual yang mendorong sistem bekerja untuk kebaikan umat.
Fenomena job hugging menunjukkan bahwa banyak orang terjebak, bukan karena mereka tidak punya ambisi, tetapi karena sistem yang berlaku menutup ruang gerak mereka.
Kapitalisme hanya melahirkan dilema. Bertahan di pekerjaan yang tak memberi makna, atau menganggur di luar sana. Sebaliknya, Islam memberikan penawaran terbaik yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama, menyediakan lapangan kerja yang adil, dan membingkai pekerjaan dalam kerangka ibadah.
Wallahu a'lam bisshawab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.

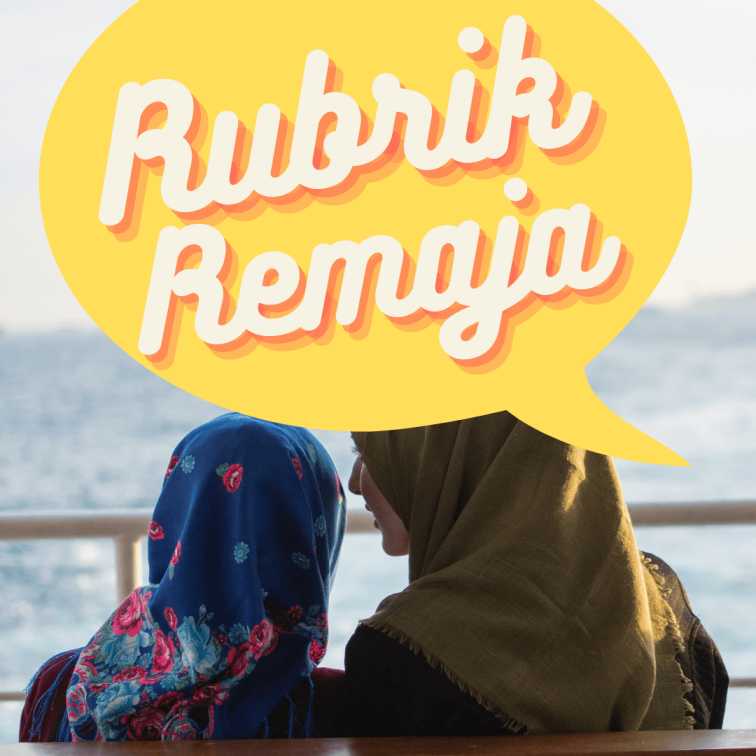




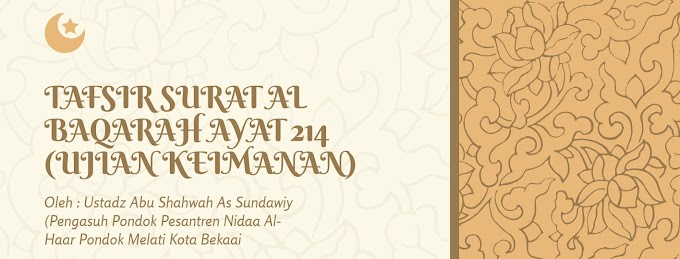


0 Komentar