Oleh : Kanti Rahmillah, M.Si (Pengamat Kebijakan Publik)
Sudah 80 tahun dunia memperingati Hari Pangan Sedunia (World Food Day), namun hingga kini angka kelaparan global masih tinggi. Padahal, momen ini sejatinya diperingati untuk meningkatkan kesadaran bahwa akses terhadap makanan bergizi merupakan hak dasar setiap manusia.
Data terbaru FAO (2025) menunjukkan sekitar 673 juta orang di dunia masih hidup dalam kelaparan, sementara 900 juta orang dewasa mengalami obesitas. Fokus peringatan Hari Pangan tahun ini adalah seruan untuk memperkuat kerja sama global dalam membangun sistem produksi pangan yang berkelanjutan di tengah krisis iklim dan ketimpangan ekonomi yang kian dalam.
Indonesia memiliki sekitar 17,3 juta penduduk yang hidup dalam kelaparan, menempatkan Indonesia di peringkat ke-70 dari 123 negara dengan kategori kelaparan sedang. Angka tersebut menjadi paradoks ketika Indonesia justru menempati peringkat ke-4 dunia sebagai penyumbang terbesar food loss dan food waste.
Di dalam negeri, perayaan Hari Pangan Sedunia diwarnai dengan aksi unjuk rasa di berbagai daerah—mulai dari Jakarta, Bogor, Bali, Banten, hingga Sulawesi Barat. Aksi tersebut diinisiasi oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) yang menyerukan bahwa reforma agraria adalah kunci untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah yang berakar sejak masa kolonial masih berlangsung hingga kini. Inilah yang menjadi pemicu konflik agraria dan berujung pada krisis pangan.
Sementara itu, FAO (Food and Agriculture Organization)—badan khusus PBB yang bertujuan mengatasi kelaparan dan meningkatkan ketahanan pangan global—sering dianggap berjalan di tempat. Sebabnya, hingga hari ini, persoalan kelaparan tidak kunjung terselesaikan. Hal ini terjadi karena seruan-seruan FAO masih berkutat pada isu teknis seperti produksi, distribusi, dan kerja sama antarnegara yang bersifat normatif. Semua itu belum menyentuh akar persoalan mendasar yang sesungguhnya menjadi sumber dari ketimpangan pangan global.
Kapitalisme Global dan Akar Ketimpangan
Kelaparan global bukan disebabkan oleh kurangnya produksi pangan, melainkan oleh ketimpangan ekonomi yang semakin lebar. Distribusi yang buruk membuat keberlimpahan produksi justru menjadi masalah baru. Di satu sisi, negara-negara makmur dan kelompok kaya memiliki surplus pangan hingga banyak yang terbuang. Di sisi lain, ratusan juta orang miskin di berbagai belahan dunia kesulitan untuk makan layak.
Ketimpangan ekonomi yang tak terkendali tidak dapat dilepaskan dari sistem kapitalisme global yang diadopsi oleh hampir seluruh negara di dunia. Sistem ini menjadikan harga sebagai satu-satunya alat distribusi, sehingga kekayaan hanya berputar di antara segelintir elite. Akibatnya, masyarakat miskin kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk pangan, karena mereka tidak memiliki daya beli.
Begitu pula dengan sistem ribawi yang menopang jalannya ekonomi kapitalis. Peredaran uang berbasis bunga menjadikan sektor nonriil tumbuh pesat, sementara sektor riil tersendat. Ketika suku bunga naik, masyarakat justru menyimpan uang di bank, yang pada akhirnya memperlambat perputaran ekonomi riil dan memperdalam ketimpangan.
Dalam hal kepemilikan sumber daya, kapitalisme juga menempatkan lahan, modal, dan industri di bawah kendali individu atau korporasi besar. Kondisi ini menciptakan akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang dan menghambat akses masyarakat umum terhadap hasil ekonomi. Misalnya, pemerintah cenderung memberikan hak guna usaha ribuan hektar lahan untuk proyek food estate, ketimbang mendistribusikan tanah dalam skala kecil kepada petani gurem.
Belum lagi dalam hal sumber daya alam yang melimpah, hampir seluruhnya dikuasai oleh sektor swasta atas nama investasi. Perusahaan-perusahaan tambang—baik batubara, nikel, emas, tembaga, timah, maupun bauksit—mayoritas dimiliki pihak swasta. Alih-alih mengelola sendiri, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan seperti UU Minerba yang sangat berpihak kepada kepentingan perusahaan besar.
Delapan puluh tahun setelah FAO berdiri, dunia masih menghadapi paradoks pangan, kelimpahan di satu sisi, kelaparan di sisi lain. Selama akar masalah—yakni ketimpangan struktural dan dominasi sistem ekonomi kapitalis global—tidak disentuh, maka seruan apa pun untuk menghapus kelaparan hanya akan menjadi slogan tahunan tanpa perubahan nyata.
Kejahatan Global
FAO menyebutkan bahwa tingkat kelaparan paling parah terjadi di wilayah-wilayah konflik. Sekitar 70–80 persen populasi yang mengalami kelaparan ekstrem hidup di negara atau kawasan yang tengah menghadapi konflik bersenjata, krisis politik, atau kekacauan sosial. Di antaranya adalah Palestina (Gaza dan Tepi Barat), Suriah, Somalia, Sudan, Yaman, Kongo, Mali, dan Nigeria.
FAO menegaskan bahwa konflik sering kali berakar pada ketimpangan ekonomi dan perebutan sumber daya alam. Salah satu contoh paling jelas adalah invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Meski secara resmi disebut sebagai upaya menggulingkan rezim Saddam Hussein, banyak analisis menilai bahwa invasi tersebut sejatinya merupakan strategi untuk mengamankan cadangan minyak terbesar kedua di dunia. Buktinya, pascaperang menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan minyak asal Amerika memperoleh kontrak besar dalam eksploitasi migas di Irak.
Hal serupa juga terjadi di Palestina. Baik di Gaza maupun Tepi Barat, perampasan lahan dan sumber daya telah menyebabkan rakyat Palestina kehilangan ruang hidupnya. Blokade berkepanjangan dan penghancuran infrastruktur pertanian membuat penduduk sipil tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dasar mereka. Kondisi kelaparan akut di Palestina adalah akibat langsung dari penjajahan dan kekerasan struktural yang berlangsung terus-menerus.
Ini adalah bentuk kejahatan global yang seharusnya dihentikan. FAO memang telah menyerukan peningkatan bantuan kemanusiaan di Palestina — bukan hanya berupa makanan siap saji, tetapi juga bantuan pertanian seperti benih, pakan, dan alat produksi — serta gencatan senjata segera agar bantuan dapat masuk dengan aman. Namun, semua seruan tersebut tidak mampu menyelesaikan akar persoalan kelaparan akut di Gaza, karena serangan dan blokade militer terus berlangsung, sementara dunia memilih diam. Tidak ada negara yang benar-benar berani menentang dominasi Amerika Serikat yang mendukung agresi tersebut.
Inilah nestapa dunia di bawah hegemoni kapitalisme global. Kejahatan global yang menelan jutaan nyawa dan membuat jutaan manusia hidup dalam kelaparan akut tidak dapat dihentikan, karena sistem ekonomi dan politik dunia kini tunduk pada logika keuntungan dan kekuasaan. Bahkan jika kita menelusuri sejarahnya, lahirnya FAO sendiri tidak dapat dilepaskan dari konteks upaya “tambal sulam” kapitalisme global pasca-Perang Dunia II.
Krisis pangan yang melanda Eropa, Asia, dan Afrika setelah perang mendorong didirikannya FAO di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 16 Oktober 1945. Sejak awal, Amerika Serikat menjadi salah satu penyumbang dana terbesar FAO, sekitar 20–25 persen dari total anggaran. Akibatnya, arah kebijakan FAO kerap selaras dengan kepentingan ekonomi dan politik AS, bahkan dalam isu-isu kemanusiaan.
Karena itu, tidak mengherankan jika FAO sering dianggap “berjalan di tempat” dalam mencapai tujuannya: memenuhi hak pangan bagi seluruh umat manusia. Selama lembaga ini tetap berada di bawah kendali negara-negara maju yang rakus dan hegemonik, cita-cita keadilan pangan global hanya akan menjadi slogan tahunan tanpa wujud nyata.
Jaminan Pangan dalam Islam
Berbeda dengan sistem kapitalisme, tata kelola ekonomi Islam menjamin distribusi harta berputar dengan adil di seluruh lapisan masyarakat. Sistemnya yang nonribawi menjadikan pergerakan ekonomi hanya berpusat pada sektor riil, bukan spekulatif. Dalam pandangan Islam, negara berperan sebagai ra’in—pengurus dan pelindung umat—yang memastikan seluruh kebutuhan dasar rakyat, termasuk pangan, berada di bawah tanggung jawab negara.
“Setiap kalian adalah pemimpin (ra‘in), dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (khalifah) adalah pemimpin atas rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka...” (HR. al-Bukhari no. 893, Muslim no. 1829)
Islam memiliki dua mekanisme utama dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok, termasuk pangan.
Pertama, mekanisme ekonomi. Negara wajib menjaga stabilitas harga, menetapkan standar mata uang berbasis emas dan perak (dinar-dirham) agar terhindar dari fluktuasi fiat money, serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Melalui kebijakan ini, sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) mendapatkan kemudahan akses modal dan bimbingan bisnis yang adil.
Kedua, mekanisme nonekonomi. Negara harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya, sehingga setiap laki-laki yang menanggung nafkah memiliki kesempatan bekerja dengan upah yang layak. Bagi individu yang tetap kesulitan mengakses kebutuhan pokok melalui mekanisme ekonomi, negara akan menyalurkan bantuan langsung untuk memastikan tidak ada satu pun warga yang kelaparan.
Khilafah Sebagai Pelindung Umat
“Sesungguhnya imam (pemimpin) adalah junnah (perisai). Umat berperang di belakangnya dan berlindung dengannya.” (HR. al-Bukhari no. 2957, Muslim no. 1841)
Dalam sistem Islam, Khilafah berfungsi sebagai negara independen yang melindungi rakyatnya dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Mengingat banyaknya konflik saat ini yang terjadi di negeri-negeri Muslim, keberadaan seorang khalifah akan memastikan tidak ada kekuatan asing yang dapat masuk, menghancurkan negeri, apalagi menghilangkan nyawa penduduk tanpa hak.
Dengan sistem seperti itu, tidak akan ada wilayah yang mengalami kelaparan akut seperti Palestina akibat agresi dan penjajahan. Sayangnya, hari ini Khilafah belum tegak, sehingga umat Islam di berbagai belahan dunia harus menghadapi ancaman dan penderitaan tanpa pelindung hakiki.
Selain memberikan perlindungan, Khilafah juga sangat memperhatikan nasib negara-negara yang tertimpa musibah. Dalam sejarah, khalifah dikenal cepat dan tulus dalam memberikan bantuan. Salah satu contohnya adalah Khalifah Sultan Abdul Majid I dari Daulah Utsmaniyah yang mengirimkan bantuan besar kepada rakyat Irlandia saat negeri itu dilanda wabah kelaparan hebat pada abad ke-19.
Khatimah
Wahai kaum Muslimin, sesungguhnya penyebab utama kelaparan akut di dunia adalah keberadaan negara-negara makmur yang mengemban dan menyebarkan ideologi kapitalisme. Negara-negara ini menjajah dengan sistem tersebut sekaligus mengklaim bahwa kapitalisme adalah sistem terbaik untuk kemanusiaan—padahal faktanya, sistem ini justru menciptakan penderitaan dan ketimpangan global.
Maka, adalah kebodohan nyata apabila umat Islam berharap kapitalisme mampu menyelesaikan persoalan yang justru ditimbulkannya sendiri. Hari Pangan Sedunia tidak akan membawa makna apa pun jika kaum Muslim tidak menyampaikan kepada dunia bahwa akar krisis pangan global terletak pada penerapan sistem kapitalisme, dan satu-satunya solusi hakiki adalah kembalinya kehidupan Islam di bawah naungan Khilafah Islamiyah.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.

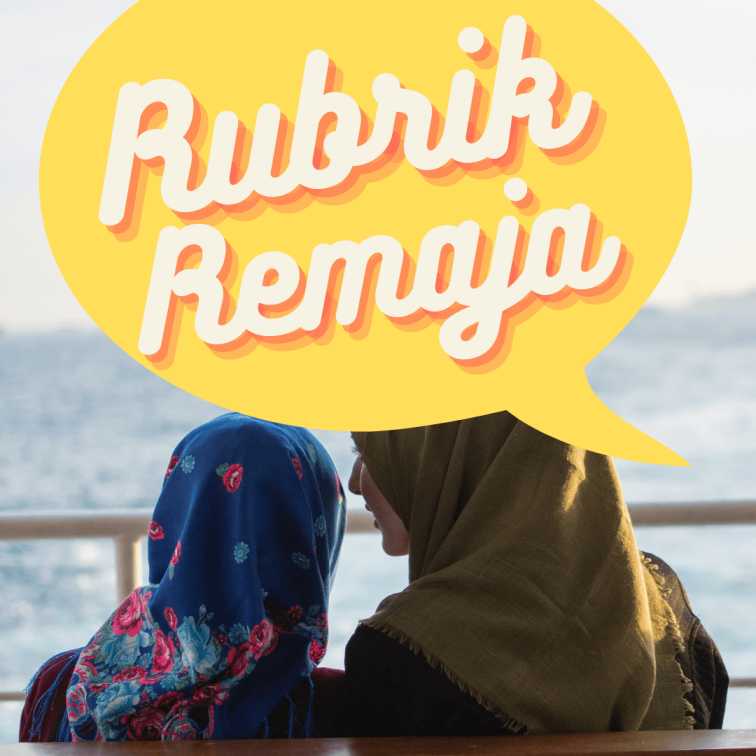




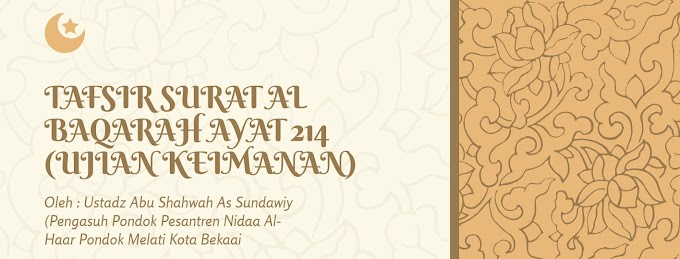


0 Komentar